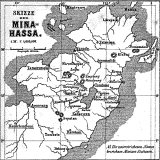Laporan Denni Pinontoan
Sebuah Wisata Kuliner di Kawangkoan

Kota Kecil Kawangkoan, sebuah kawasan yang tak terlalu berubah akibat modernisasi. Warga di sini masih setia dengan beberapa adat istiadat Minahasa. Berbicara pun, mereka masih kental dengan Bahasa Manado Melayu dan Bahasa Minahasa (makatana) rumpun Toutemboan. Hubungan kekerabatan antar warga pun masih kental.
Kota Kawangkoan yang termasuk di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Minahasa ini, terletak di daerah pegunungan, yang udaranya relatif masih sejuk seolah-seolah tidak sedang bermasalah dengan global warming. Ke Kota Kawangkoan, dari Kota Manado, kita membutuhkan waktu kurang lebih sejam. Kalau dari Kota Tomohon, waktunya kira-kira hanya setengah jam atau kurang.
Dari arah Kota Manado dan Tomohon, memasuki Kota Kawangkoan, kita akan melihat beberapa gua Jepang, di sebuah tempat yang disebut Ranowangko. Bahkan, di kelurahan Sendangan, ada Gua Lima Puluh Kamar. Disebut Gua Lima Puluh Kamar, karena jumlah kamar di gua ini konon berjumlah 50 buah. Objek wisata ini sebenarnya menarik, tapi sayang pemerintah kabupaten belum menata dan mengolahnya secara serius. Di kelurahan Kinali ada juga Air Panas, yang bagus untuk terapi kesehatan.
Tapi kali ini kita tidak akan ke tempat-tempat wisata itu. Sebab, Anda pasti pernah dengar, bahwa Kota Kawangkoan terkenal dengan sebutannya sebagai Kota Kacang. Ini terkait dengan yang khas di kota ini, yaitu Kacang Sangrai yang gurih, lezat dan renyah. Kacang Sangrai pun menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga di kota kelahiran sejumlah tokoh pergerakan ini. Ada warga yang berprofesi menjual dan ada warga yang bekerja memproduksi kacang Sangrainya. “Tapi sebenarnya, kacang-kacang itu tidak semua ditanam di Kawangkoan ini. Banyak di antaranya yang diambil dari luar Kawangkoan, misalnya Tompaso,” ujar Doni Masengi, warga Kelurahan Talikuran, yang bersedia menemani sulutlink berwisata kuliner kali ini.
Kebanyakan kacang sangrai bisa kita temui di pusat Kota Kawangkoan. Jenis kacang Sangrai yang dijual di kota ini ada dua, yaitu kacang biasa, tapi dan kacang yang banyak diminati pembeli, yaitu kacang jenis belimbing. “Kalau kacang sangarai jenis belimbing, rasanya lebih gurih, dan buah kacangnya lebih besar dan padat. Tapi harganya memang lumayan juga, sekitar Rp. 7000 sampai Rp. 7500 perliter,” ujar Doni. Kami pun coba menyantapnya. Wow, memang enak.
***
 Para pelancong yang singga di kota ini sering menjadikan kacang sangrai ini sebagai oleh-oleh untuk sanak family yang menunggu di rumah. Selain kacang sangrai ada juga jenis jajanan lainnya, misalnya halua yang terbuat dari gula merah dan kacang, kemudian bagea, kue kering yang terbuat sari sagu, dan ada juga kacang goyang. Semua kue kering ini memang khas Minahasa. “Kebanyakan pembeli di sini, selain warga yang melewati kota ini setelah bepergian dari kota lain, tapi ada juga para turis yang ingin menikmati kuliner khas Minahasa,” jelas Doni.
Para pelancong yang singga di kota ini sering menjadikan kacang sangrai ini sebagai oleh-oleh untuk sanak family yang menunggu di rumah. Selain kacang sangrai ada juga jenis jajanan lainnya, misalnya halua yang terbuat dari gula merah dan kacang, kemudian bagea, kue kering yang terbuat sari sagu, dan ada juga kacang goyang. Semua kue kering ini memang khas Minahasa. “Kebanyakan pembeli di sini, selain warga yang melewati kota ini setelah bepergian dari kota lain, tapi ada juga para turis yang ingin menikmati kuliner khas Minahasa,” jelas Doni.
Tapi di kota ini bukan hanya kuliner yang kering-kering. Sajian makanan yang basah-basah juga terdapat di kota ini. Selain terkenal dengan kacang sangrai, kota Kawangkoan juga terkenal dengan Bakpao atau Biapong khas Kawangkoan. Ada Biapong yang isinya daging babi, ada juga biapong yang isinya temo. Sejumlah rumah kopi di pusat kota kawangkoan menjadikan Biapong sebagai menu andalannya. Dan, biapong memang enak disantap bersama dengan kopi susu, teh susu, atau kopi pahit manis saja. Selain biapong, ada juga roti bakar. Roti bakarnya memang lezat, karena dibakar dengan menggunakan bara tempurung.
Ada sekitar 3 rumah kopi besar di pusat kota Kawangkoan, yaitu rumah kopi Sarinah, Toronata dan Gembira. Setiap pagi dan sore rumah-rumah kopi ini dipadati oleh para pengunjungnya. Sambil minum kopi susu dan makan biapong para pengunjung juga menggunakan waktu santai itu untuk bacirita banyak hal. Mulai dari soal bola, politik, sampai urusan dagang, blante (barter), misalnya. “Para pengunjung rumah-rumah kopi ini, selain yang dari luar, sekedar untuk singgah dan membeli jajanan, tapi juga warga Kawangkoan yang rutin ke sini sering menjadikan rumah-rumah kopi ini untuk baciria banyak hal. Ada yang bicara tentang bola, blante, bahkan juga soal politik,” kata Doni lagi.
Setelah puas dengan berbelanja oleh-oleh, dan minum kopi serta maka biapong, saatnya kita makan nasi dan berbagai jenis menu khas Minahasa, seperti ragey, RE, Tinoransak, saroy pait, dan lain sebagainya. Di Kota Kawangkoan ada beberapa rumah makan yang menyediakan menu-menu ini.
Di ujung kota ini, ada rumah makan yang cukup bagus dengan sajian menu yang lengkap, tapi bisa dijangkau oleh kantong yang pas-pasan. Di rumah makan “eleny” kita bisa memesan beragam menu khas Minahasa. Tempatnya cukup strategis, pemandangan pegunungan menambah kekhasan rumah makan ini. Di rumah makan ini tersedia ragey, sebagai menu andalan, RW, Tinoransak, saroy pait, bia santang dan lain-lain. “Ragey (sejenis sate, tapi daging babinya lebih besar), adalah khas Kawangkoan. Sekarang banyak rumah makan di luar Kawangkoan yang telah menjadikannya sebagai menu andalan,” jelas Doni.
Lengkap sudah wisata kuliner kita kali ini. Kacang Sangrai sudah, biapong sudah, ragey sudah. Apalagi? Saatnya kita pulang. Kapan-kapan kita balik lagi ke sini, berwisata ke Gua Lima Puluh Kamar atau mandi air panas di Kinali.
(Diambil dari www.leput412.blogspot.com)


 Para pelancong yang singga di
Para pelancong yang singga di